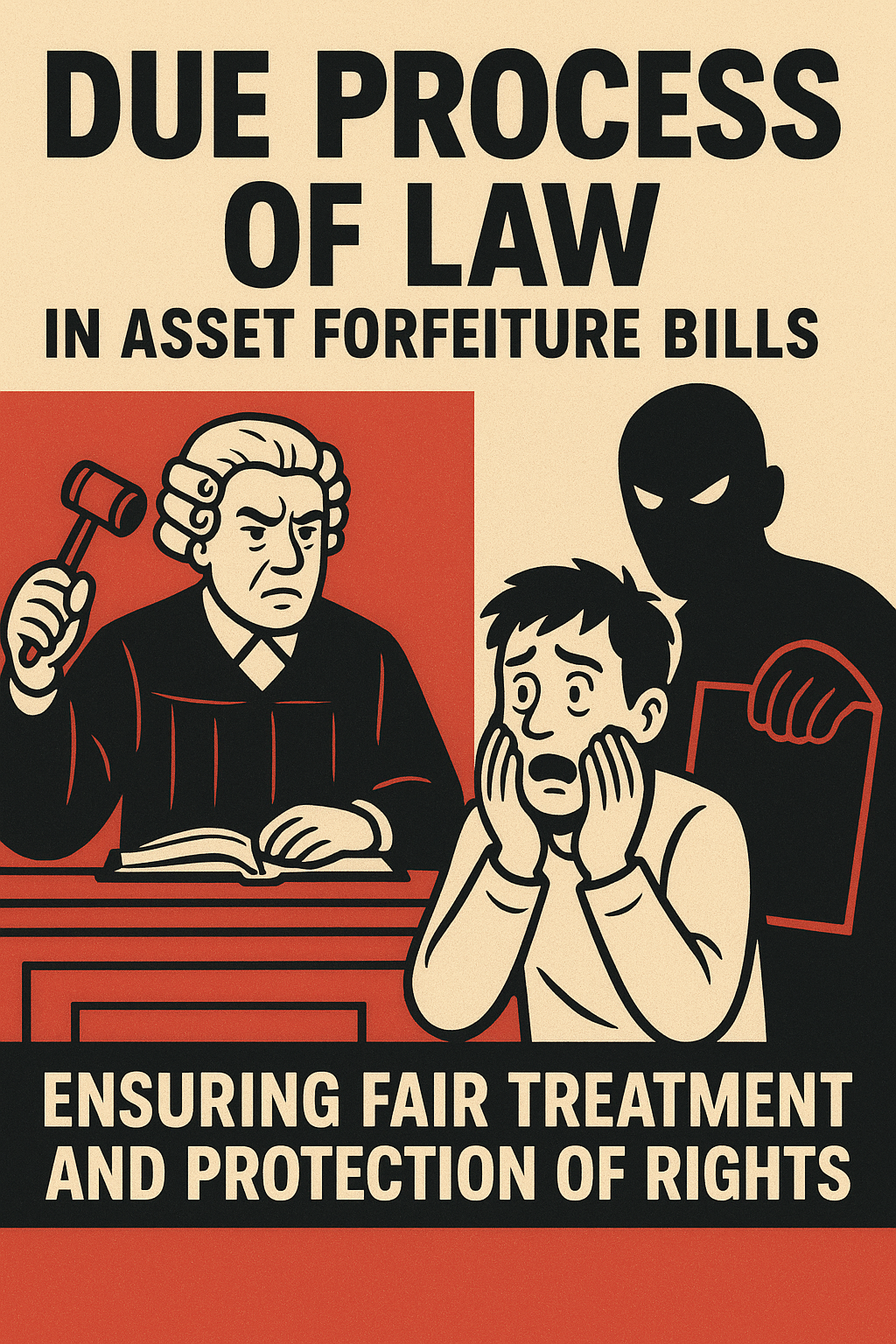dialektis.id – Setelah 18 tahun tertunda, RUU kontroversial ini akhirnya masuk prioritas legislasi. Namun muncul pertanyaan krusial, Bisakah negara merampas aset tanpa vonis pidana tanpa melanggar prinsip keadilan prosedural ?
Uang Rp 109 triliun cukup untuk membangun 10.900 sekolah atau 2.180 rumah sakit. Sayangnya, sebanyak itu aset hasil korupsi yang menguap dalam lima tahun terakhir karena keterbatasan hukum Indonesia.
Di Kalimantan Barat, gambaran serupa terjadi. Dari 12 kasus korupsi besar yang divonis dalam periode 2018-2023, hanya 15% aset yang berhasil dikembalikan ke negara. Sisanya ? Tetap aman di tangan koruptor atau keluarganya.
Menurut survei Litbang Kompas Mei 2025, inilah yang mendorong 92,5% publik untuk mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang sudah tertunda 18 tahun.
Dalam sistem hukum modern, prinsip due process of law adalah jantung keadilan karena tidak ada hukuman tanpa proses yang adil, tidak ada perampasan hak tanpa kesempatan membela diri. Namun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang kini masuk Prolegnas Prioritas 2025 mengusung konsep yang tampak paradoks yakni merampas aset tanpa memidana pelakunya.
Inilah dilema hukum abad ke-21 yang kini dihadapi Indonesia, yakni bagaimana memerangi korupsi canggih yang merugikannegara Rp 109 triliun dalam lima tahun terakhir, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental negara hukum ?
Ketika Hukum Pidana Konvensional Gagal
Sistem peradilan pidana Indonesia saat ini menghadapi paradoks. Di satu sisi, kerugian negara akibat korupsi tahun 2022 mencapai Rp 48,786 triliun. Di sisi lain, yang berhasil dikembalikan hanya 7,83% atau Rp 3,821 triliun.
“Angka ini bukan hanya soal uang. Ini menunjukkan kegagalan sistemik dalam memenuhi aspek keadilan restoratif yang mengembalikan kerugian kepada korban, dalam hal ini negara dan rakyat,” ungkap Prof. Dr. Saldi Isra, pakar hukum tata negara.
Masalahnya terletak pada prinsip in personam dalam hukum pidana yang berfokus pada orangnya. Jika pelaku meninggal, kabur, atau tidak dapat dibuktikan kesalahannya secara pidana, aset hasil kejahatan tetap aman. Proses pidana bisa memakan waktu bertahun-tahun, sementara aset berpindah tangan dalam hitungan jam.
Non-Conviction Based Forfeiture
RUU Perampasan Aset mengadopsi pendekatan in rem yang berfokus pada bendanya, bukan orangnya melalui konsep non-conviction based asset forfeiture (NCB). Negara dapat merampas aset yang diduga hasil kejahatan tanpa menunggu vonis pidana.
Dr. Yunus Husein, mantan Kepala PPATK, menjelaskan, “Ini bukan konsep aneh. Sudah diterapkan di 50 negara lebih, termasuk Australia, Inggris, dan Singapura. Bahkan Indonesia sudah meratifikasi UNCAC 2003 yang mendorong mekanisme ini.” Namun di sinilah muncul pertanyaan krusial tentang due process of law.
Presumption of Innocence vs Presumption of Guilt terhadap Aset
Dalam hukum pidana, seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Namun dalam NCB, aset dianggap sebagai hasil kejahatan sampai pemiliknya membuktikan sebaliknya. “Ini bukan pelanggaran asas praduga tak bersalah karena yang diadili adalah asetnya, bukan orangnya. Beban pembuktian terbalik sudah ada dalam UU Tindak Pidana Korupsi kita,” jelas Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar dari PUKAT UGM.
Lebih lanjut, Bivitri Susanti dari PSHK mengingatkan bahwa “dalam praktik, pemisahan ini tidak jelas, merampas aset seseorang tanpa proses pidana yang tuntas tetap membawa stigma sosial dan konsekuensi yang serius,” ujarnya.
Right to Property vs Public Interest
Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 menjamin hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang. Namun Pasal 28J juga mengatur pembatasan hak untuk kepentingan umum. “Di sinilah tensionnya. RUU ini harus sangat hati-hati merancang mekanisme yang memastikan perampasan aset benar-benar untuk kepentingan umum dan dilakukan dengan prosedur yang adil,” tegas Prof. Satjipto Rahardjo.
Access to Justice, Hak Membela Diri yang Memadai
Due process of law bukan hanya soal ada tidaknya pengadilan, tapi apakah prosesnya fair. Dalam draft RUU saat ini, pemilik aset punya hak untuk mendapat pemberitahuan resmi terkait mengajukan keberatan, didengar keterangannya di pengadilan, mengajukan bukti, dan didampingi kuasa hukum
“Ini penting. Tapi detailnya masih abu-abu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan ? Bagaimana jika pemilik ada di luar negeri ? Apakah ada legal aid bagi yang tidak mampu bayar pengacara ? Ini semua harus jelas,” desak Zaenur Rohman dari PUKAT UGM.
Draf RUU Saat Ini Menunjukkan Gap dalam Due Process of Law
Analisis PSHK terhadap draft terakhir RUU Perampasan Aset (2023) menemukan beberapa kelemahan krusial. Pertama, draft tidak menyebutkan batas minimum nilai aset yang bisa dirampas. Artinya, secara teori, rumah senilai Rp 500 juta pun bisa dirampas jika dianggap hasil kejahatan. “Tanpa threshold, ini membuka pintu penyalahgunaan. Harus ada batasan jelas, misalnya minimal Rp 5 miliar, agar tidak digunakan untuk kasus-kasus kecil,” usul Ronald Rofiandri.
Kedua, draft menempatkan kejaksaan sebagai penyidik, penuntut, dan pengelola aset hasil rampasan. “Ini merupakan textbook conflict of interest. Harusnya ada lembaga independen untuk pengelolaan aset, yang diawasi oleh parlemen dan publik,” kritik ICW.
Ketiga, draft menyebutkan “tindak pidana tertentu dengan ancaman pidana 4 tahun atau lebih.” Hal ini sangat luas, mencakup ratusan jenis tindak pidana.” Mestinya dibatasi untuk kejahatan serius, seperti korupsi, pencucian uang, narkotika, terorisme. Jangan sampai diperluas sewenang-wenang,” tegas Zainal Arifin Mochtar.
Keempat, tidak ada klausul tegas tentang oversight mechanism, yakni siapa yang mengawasi pelaksanaan perampasan aset ?“Tanpa pengawasan independen, due process hanya menjadi jargon. Harus ada ombudsman khusus atau komisi independen yang mengawasi,” saran PSHK.
Kelima, bagaimana jika aset itu sudah dijual ke pihak ketiga yang beritikad baik ? Draft tidak memberikan mekanisme perlindungan yang jelas “Ini bisa mengganggu kepastian hukum dalam transaksi bisnis. Pembeli rumah atau kendaraan bisa kehilangan hartanya tanpa salah apa-apa,” ungkap pengacara Hotman Paris Hutapea.
Mantan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo pernah menyatakan, “Kami butuh instrumen ini. Tapi kami juga sadar betapa mudahnya kewenangan besar disalahgunakan tanpa check and balance.” Seorang hakim Pengadilan Tipikor yang meminta anonim mengaku, khawatir bahwa dalam praktiknya tekanan politik sangat kuat. Jika RUU ini tidak punya safeguard yang ketat, hakim bisa dipaksa memutus berdasarkan tekanan, bukan bukti.
Aksi massa “17+8 Tuntutan Rakyat” pada Agustus 2025 yang melibatkan mahasiswa, NGO, hingga influencer berhasil mendorong RUU masuk Prolegnas Prioritas. BEM SI, ICW, TII, dan koalisi masyarakat sipil kompak menuntut pengesahan. Namun mereka juga menyadari risiko.
Dalam pertemuan dengan DPR tanggal 10 September 2025, koalisi masyarakat sipil menyampaikan catatan kritis. “Kami dukung pengesahan, tapi dengan syarat, substansi RUU harus menjamin due process of law. Kami tidak mau instrumen antikorupsi berubah jadi instrumen represif,” tegas perwakilan ICW.
Presiden Prabowo, Komitmen atau Lip Service
Dalam pidato 1 Mei 2025, Presiden Prabowo menyatakan, “Kita harus punya instrumen kuat untuk mengembalikan uang rakyat, tapi harus dilakukan dengan cara yang beradab dan konstitusional.” Kata konstitusional di sini menjadi kunci. Artinya, pemerintah menyadari bahwa RUU ini harus selaras dengan prinsip-prinsip UUD NRI 1945, termasuk due process of law. Namun skeptisisme tetap ada.
“Kami sudah dengar janji serupa dari SBY dan Jokowi. Sekarang buktinya, apakah pemerintah dan DPR benar-benar akan membahas dengan serius, melibatkan partisipasi publik, dan memastikan substansinya tepat?” tanya Bivitri Susanti.
Relevansi dengan Dinamika Politik Hukum Saat Ini
RUU ini lahir di tengah konteks politik hukum yang kompleks. Revisi UU KPK (2019) yang melemahkan komisi antikorupsi membuktikan bahwa instrumen hukum bisa dipakai untuk melindungi kepentingan elite, bukan rakyat. Pembahasan RKUHAP (2024-2025) yang bersamaan dengan RUU Perampasan Aset harus diharmonisasikan agar tidak saling bertentangan. Kasus-kasus kriminalisasi terhadap pengkritik pemerintah menunjukkan rentannya due process dalam praktik penegakan hukum Indonesia.
“Konteks ini membuat kita harus ekstra hati-hati. RUU Perampasan Aset bisa jadi game changer dalam pemberantasan korupsi, atau bisa jadi instrumen represif baru. Tergantung bagaimana substansinya dirancang,” analisis Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar.
Indonesia punya sejarah kelam legislasi yang tergesa-gesa, seperti UU Ciptaker (2020) yang disahkan dengan proses cacat prosedural, akhirnya dibatalkan MK karena tidak memenuhi due process of law dalam pembentukannya.
Pasal-pasal karet pada UU ITE yang lahir tanpa pengawalan ketat kini jadi alat kriminalisasi. Selanjutnya, pasal imunitas yang berlebihan pada UU MD3 guna melindungi anggota DPR dari jeratan hukum. “Jangan sampai RUU Perampasan Aset mengulang kesalahan yang sama. Proses pembahasannya harus partisipatif, transparan, dan sungguh-sungguh mempertimbangkan aspek konstitusionalitas,” ingat Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM.
Suara Berbeda, Yang Menolak RUU
Tidak semua pihak mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset ini. Asosiasi Pengacara Indonesia (Peradi) menyatakan keberatan, “Konsep NCB bertentangan dengan prinsip fundamental hukum pidana. Ini membuka pintu kesewenang-wenangan. Sejumlah pengusaha juga khawatir dengan ketidakpastian hukum ini karena bisa mengganggu iklim investasi. Pengusaha takut asetnya tiba-tiba disita dengan dalih mencurigakan.”
Namun ICW membantah, “Jika aset diperoleh secara sah, tidak ada yang perlu ditakutkan”. Yang takut justru mereka yang punya aset tidak wajar. Ini merupakan tujuan RUU ini.”
Dr. Oce Madril dari PUKAT UGM menegaskan, “Kami pro pengesahan RUU ini karena Indonesia butuh instrumen kuat untuk pemulihan aset. Tapi kami juga pro due process of law. Keduanya tidak bertentangan jika RUU dirancang dengan cermat. Karena kunci keberhasilannya terletak pada keseimbangan. Artinya, RUU Perampasan Aset cukup kuat untuk memburu aset korupsi yang disembunyikan, namun cukup terkontrol agar tidak melanggar hak asasi manusia.”
“Rule of law” bukan hanya soal ada tidaknya aturan, tapi apakah aturan itu adil dan dijalankan secara adil. RUU Perampasan Aset harus memenuhi standar ini,” tutup Prof. Satjipto Rahardjo. Setelah 18 tahun penantian, RUU Perampasan Aset kini berada di persimpangan. Disahkan dengan substansi yang tepat, pengaturan ini bisa menjadi senjata ampuh dalam melawan korupsi sambil tetap menghormati due process of law. Disahkan dengan tergesa-gesa dan cacat substansi, pengaturan ini tentu bisa jadi bumerang yang melukai prinsip-prinsip negara hukum itu sendiri. Pilihan ada di tangan DPR dan pemerintah. Rakyat menunggu, mengawasi, dan menuntut. Karena sejatinya, pemberantasan korupsi dan perlindungan HAM bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama yakni keadilan.
Tulisan dan Karya akademik ini dibuat oleh :
Nama : Zahra Safa Marwah Karim
NIM : 25/567966/PHK/13544)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum UGM,